BarisanBerita.com,- Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran menjadi momen indah bagi orang Indonesia. Sayur Ketupat dan opor ayam jadi santapan yang ditunggu-tunggu.
Tapi, tidak untuk Soekarno kecil. Dia harus menahan semua keinginannya merayakan Pesta Raya Umat Islam itu dengan sedih.
Dia pun mengenang masa-masa pahit itu:
Masa kanak‐kanakku tidak berbeda dengan David Copperfield. Aku dilahirkan di tengah‐tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemiskinan. Aku tidak mempunyai sepatu. Aku mandi tidak dalam air yang keluar dari kran. Aku tidak mengenal sendok dan garpu. Ketiadaan yang keterlaluan demikian ini dapat menyebabkan hati kecil di dalam menjadi sedih. Dengan kakakku perempuan Sukarmini, yang dua tahun lebih tua daripadaku, kami merupakan suatu keluarga yang terdiri dari empat orang. Gaji bapak $ 25 sebulan. Dikurangi sewa rumah kami di Jalan Pahlawan 88, neraca menjadi $ 15 dan dengan perbandingan kurs pemerintah $ 3,60 untuk satu dolar dapatlah dikira‐kira betapa rendahnya tingkat penghidupan keluarga kami. Ketika aku berumur enam tahun kami pindah ke Mojokerto. Kami tinggal di daerah yang melarat dan keadaan tetangga‐tetangga kami tidak berbeda dengan keadaan sekitar itu sendiri, akan tetapi mereka selalu mempunyai sisa uang sedikit untuk membeli pepaya atau jajan lainnya.
Tapi aku tidak. Tidak pernah. Lebaran adalah hari besar bagi umat Islam, hari penutup dari bulan puasa, pada bulan mana para penganutnya menahan diri dari makan dan minum ataupun tidak melewatkan sesuatu melalui mulut mulai dari terbitnya matahari sampai ia terbenam lagi. Kegembiraan di hari Lebaran sama dengan hari Natal. Hari untuk berpesta dan berfitrah. Akan tetapi kami tak pernah berpesta maupun mengeluarkan fitrah. Karena kami tidak punya uang untuk itu.
Di malam sebelum Lebaran sudah menjadi kebiasaan bagi kanak‐kanak untuk main petasan. Semua anak‐anak melakukannya dan di waktu itupun mereka melakukannya. Semua, kecuali aku. Di hari Lebaran lebih setengah abad yang lalu aku berbaring seorang diri dalam kamar‐ tidurku yang kecil yang hanya cukup untuk satu tempat tidur. Dengan hati yang gundah aku mengintip keluar arah ke langit melalui tiga buah lubang udara yang kecil‐kecil pada dinding bambu. Lubang udara itu besarnya kira‐kira sebesar batu bata. Aku merasa diriku sangat malang. Hatiku serasa akan pecah.
Di sekeliling terdengar bunyi petasan berletusan disela oleh sorak‐sorai kawan‐kawanku karena kegirangan. Betapa hancur luluh rasa hatiku yang kecil itu memikirkan, mengapa semua kawan‐kawanku dengan jalan bagaimanapun dapat membeli petasan yang harganya satu sen itu — dan aku tidak!.
Alangkah dahsyatnya perasaan itu. Mau mati aku rasanya. Satu‐satunya jalan bagi seorang anak untuk mempertahankan diri ialah dengan melepaskan sedu‐sedan yang tak terkendalikan dan meratap diatas tempat tidurnya. Aku teringat ketika aku menangis kepada ibu dan mengumpat, “Dari tahun ke tahun aku selalu berharap‐harap, tapi tak sekalipun aku bisa melepaskan mercon.” Aku sungguh menyesali diriku sendiri.
Kemudian di malam harinya datang seorang tamu menemui bapak. Dia memegang bungkusan
kecil ditangannya. “Ini,” katanya sambil mengulurkan bingkisan itu kepadaku. Aku sangat gemetar karena terharu mendapat hadiah itu, sehingga hampir tidak sanggup membukanya. Isinya petasan. Tak ada harta, lukisan ataupun istana di dunia ini yang dapat memberikan kegembiraan kepadaku seperti pemberian itu. Dan kejadian ini tak dapat kulupakan untuk selama‐lamanya.
Kami sangat melarat sehingga hampir tidak bisa makan satu kali dalam sehari. Yang terbanyak kami makan ialah ubi kayu, jagung tumbuk dengan makanan lain. Bahkan ibu tidak mampu membeli beras murah yang biasa dibeli oleh para petani. Ia hanya bisa membeli padi. Setiap pagi ibu mengambil lesung dan menumbuk, menumbuk, tak henti‐hentinya menumbuk butiran‐butiran berkulit itu sampai menjadi beras seperti yang dijual orang di pasar.
“Dengan melakukan ini aku menghemat uang satu sen,” katanya kepadaku pada suatu hari ketika sedang bekerja dalam teriknya panas matahari sampai telapak tangannya merah dan melepuh. “Dan dengan uang satu sen kita dapat membeli sayuran, nak.”
Semenjak hari itu dan seterusnya selama beberapa tahun kemudian, setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah aku menumbuk padi untuk ibuku. Kemelaratan seperti yang kami derita menyebabkan orang menjadi akrab.
Apabila tidak ada barang mainan atau untuk dimakan, apabila nampaknya aku tidak punya apa‐apa di dunia ini selain daripada ibu, aku melekat kepadanya karena ia adalah satu‐satunya sumber pelepas kepuasan hatiku. Ia adalah ganti gula‐gula yang tak dapat kumiliki dan ia adalah semua milikku yang ada di dunia ini. Yah, ibu mempunyai hati yang begitu besar dan mulia.
Dalam pada itu bapakku seorang guru yang keras. Sekalipun sudah berjam‐jam, ia masih tega menyuruhku belajar membaca dan menulis. “Hayo, Karno, hafal ini luar kepala. Ha—Na—Ca—Ra— Ka Hayo, Karno, hafal ini; A‐B‐C‐D‐E” dan terusmenerus sampai kepalaku yang malang ini merasa sakit. Lagi‐lagi kemudian, “Hayo Karno, ulangi abjad Hayo, Karno, baca ini Karno, tulis itu” Tapi ayahku mempunyai keyakinan, bahwa anaknya yang lahir di saat fajar menyingsing itu kelak akan menjadi orang.
Kalau aku berbuat nakal —ini jarang terjadi— dia menghukumku dengan kasar. Seperti di pagi itu aku memanjat pohon jambu di pekarangan rumah kami dan aku menjatuhkan sarang burung. Ayah menjadi pucat karena marah. “Kalau tidak salah aku sudah mengatakan padamu supaya menyayangi binatang,” ia menghardik. Aku bergoncang ketakutan. “Ya, Pak.” “Engkau dapat menerangkan arti kata‐kata: ‘Tat Twan Asi, Tat Twam Asi’ ?”, “Artinya ‘Dia adalah Aku dan Aku adalah dia; engkau adalah Aku dan Aku adalah engkau.’ “Dan apakah tidak kuajarkan kepadamu bahwa ini mempunyai arti yang penting?” Ya, Pak. Maksudnya, Tuhan berada dalam kita semua,” kataku dengan patuh.
Dia memandang marah kepada pesakitannya yang masih berumur tujuh tahun. “Bukankah engkau sudah ditunjuki untuk melindungi makhluk Tuhan?”, “Ya, Pak.”,”Engkau dapat mengatakan apa burung dan telor itu ?”,”Ciptaan Tuhan,” jawabku dengan gemetar, “tapi dia jatuh karena tidak disengaja. Tidak saja sengaja. “Sekalipun dengan permintaan ma’af demikian, bapak memukul pantatku dengan rotan. Aku seorang yang baik laku, akan tetapi bapak menghendaki disiplin yang keras dan cepat marah kalau aturannya tidak dituruti.
Aku segera mencari permainan yang tidak usah mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Dekat rumah kami tumbuh sebatang pohon dengan daunnya yang lebar. Daun itu ujungnya kecil, lalu mengernbang lebar di pangkalnya dan tangkainya panjang seperti dayung. Adalah suatu hari yang gembira bagi anak‐anak, kalau setangkai daun gugur, karena ini berarti bahwa kami mempunyai permainan. Seorang lalu duduk di bagian daun yang lebar, sedang yang lain menariknya pada tangkai yang panjang itu dan permainan ini tak ubahnya seperti eretan. Kadangkadang aku menjadi kudanya, tapi biasanya menjadi kusir.
Watakku mulai berbentuk sekalipun sebagai kanak‐kanak. Aku menjadikan sungai sebagai kawanku, karena ia menjadi tempat dimana anak‐anak yang tidak punya dapat bermain dengan cuma‐cuma. Dan iapun menjadi sumber makanan. Aku senantiasa berusaha keras untuk menggembirakan hati ibu dengan beberapa ekor ikan kecil untuk dimasak. Alasan yang tidak mementingkan diri sendiri demikian itu pada suatu kali menyebabkan aku kena ganjaran cambuk.
Hari sudah mulai senja. Ketika bapakku melihat bahwa hari mulai gelap dan bocah Sukarno tidak ada dirumah, dia menuntut ibu dengan keras: “Kenapa dia bersenang‐senang tak keruan begitu lama? Apa dia tidak punya pikiran terhadap ibunya? Apa dia tidak tahu bahwa ibunya akan susah kalau terjadi kecelakaan?”,”Negeri begini kecil, Pak, tidak mungkin kita tidak mengetahui kalau terjadi ketjelakaan,” ibu menerangkan. Sekalipun demikian, bapak yang agak keras kepala marah dan ketika aku sejam kemudian melonjak‐lonjak gembira pulang dengan membawa ikan kakap untuk ibu, bapak menangkapku, merampas ikan dan semua yang ada padaku, lalu aku dirotan sejadi‐jadinya.
Tetapi ibu selalu mengimbangi tindakan disiplin itu dengan kebaikan hatinya. Oh, aku sangat mencintai ibu. Aku berlari berlindung ke pangkuan ibu dan dia membujukku. Sekalipun rumput‐rumput kemelaratan mencekik kami, namun bunga‐bunga cinta tetap mengelilingiku selalu. Aku segera menyadari bahwa kasih sayang menghapus segala yang buruk. Keinginan akan cinta kasih telah menjadi suatu kekuatan pendorong dalam hidupku.
(Sumber: Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat)






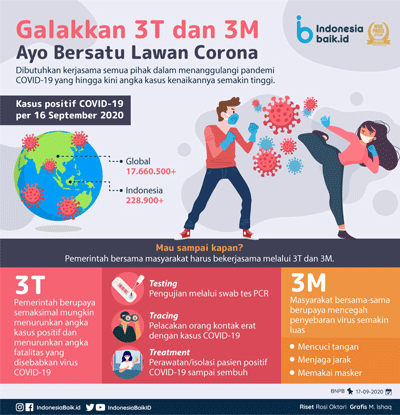
















Dead pent content material, regards for information .